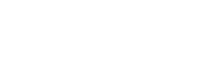Bulan Agustus selalu membawa aroma yang berbeda di udara. Ada semacam getar yang menyelinap di antara terik siang dan semilir angin sore. Di desa maupun kota, suasana perayaan kemerdekaan menyeruak dari setiap sudut: bendera merah putih berkibar anggun di depan rumah, gapura dihias meriah dengan pita dan cat warna-warni, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan di sekolah, lagu kebangsaan kembali menggema dari pengeras suara yang suaranya sedikit serak.
Namun di balik kemeriahan itu, terselip pertanyaan yang pelan-pelan mengetuk hati: bagaimana sebenarnya anak-anak memaknai cinta tanah air? Apakah bagi mereka ia hanya sebatas pesta tahunan yang meriah, atau ada sesuatu yang lebih dalam—rasa yang tumbuh diam-diam dan tinggal di hati mereka?
Bagi orang dewasa, nasionalisme kerap terbayang dalam bentuk besar dan megah: membela negara, menjaga kedaulatan, mempertahankan identitas bangsa. Tetapi bagi anak-anak, nasionalisme hadir seperti hujan gerimis di sore hari: lembut, dekat, dan menyentuh. Cinta tanah air bagi mereka mungkin terwujud dalam menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara lantang meski sedikit fals, dalam berdiri tegak di bawah matahari saat upacara bendera, dalam rasa bangga mengenakan batik di perayaan sekolah, atau dalam tawa riang saat mengikuti lomba makan kerupuk di halaman rumah. Kadang, rasa itu bahkan lahir dari hal sederhana: mencicipi soto di warung langganan, membaca komik bergambar pahlawan, atau mendengar dongeng kakek tentang zaman perjuangan.
Ketika Anak Belajar Mencintai
Nasionalisme bagi anak bukanlah hafalan yang kaku, melainkan pengalaman yang hangat. Ia bertunas dari rasa ingin tahu terhadap budaya sendiri, dari kebiasaan menghargai teman yang berbeda latar, dari interaksi sehari-hari yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah kelahiran. Dalam dunia mereka, cinta tanah air bukan slogan yang dicetak di spanduk, melainkan rasa bangga yang tumbuh pelan, melalui lagu, cerita, permainan, dan kebersamaan.
Di desa-desa, Agustus mengubah suasana. Lapangan kecil di ujung kampung berubah jadi panggung tawa. Anak-anak berlatih makan kerupuk dengan tangan diikat, menyusun strategi untuk lomba balap kelereng, atau mempersiapkan kostum parade kemerdekaan yang dijahit ibu-ibu PKK. Bagi orang dewasa, semua ini mungkin sekadar tradisi tahunan. Tapi bagi anak-anak, di sanalah benih nasionalisme ditanam: tidak lewat pidato panjang yang mereka sulit pahami, melainkan lewat sorak-sorai yang membuat hati mereka berdebar.
Heri Priyatmoko, sejarawan dari Universitas Sanata Dharma, menyebut lomba-lomba 17-an sebagai monumen ingatan kolektif rakyat. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan cara rakyat merawat sejarah dengan bahasa yang akrab. Bagi anak-anak, lomba itu adalah pintu kecil menuju dunia besar bernama Indonesia—pintu yang tidak menakutkan, melainkan mengundang mereka masuk dengan pelukan hangat.
Di tengah arus globalisasi yang deras, pendidikan karakter menjadi benteng yang tak kalah penting dari pagar batas negara. Psikolog keluarga Nurmey Nurulchaq mengingatkan bahwa anak-anak perlu merasa menjadi bagian dari bangsanya. Sebab ketika rasa memiliki itu tertanam, cinta tanah air akan tumbuh sendiri, seperti tanaman yang tak butuh dipaksa untuk mekar. Dan lomba-lomba kemerdekaan adalah pupuk yang menyuburkan benih itu—menggabungkan tawa, rasa bangga, dan kebersamaan dalam satu wadah yang manis.
Merawat Mawar
Lomba 17-an bukan sekadar adu cepat atau adu pintar. Ia adalah jam-jam berharga yang dihabiskan untuk membangun rasa memiliki. Setiap helai pita merah putih yang diikat di gapura, setiap sorak yang pecah saat kerupuk akhirnya tergigit, adalah detik-detik yang menempel di ingatan. Seperti mawar yang dirawat setiap hari, cinta tanah air pun bertumbuh dari waktu, perhatian, dan kehangatan yang kita curahkan.
Antonine de Saint-Exupéry pernah menulis dalam The Little Prince: “It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.” Sesuatu menjadi berharga bukan karena bentuknya, melainkan karena waktu dan cinta yang telah kita berikan kepadanya. Begitu pula dengan nasionalisme pada anak, ia tidak lahir dari perintah, melainkan dari pengalaman kecil yang diulang-ulang, hingga akhirnya menjadi bagian dari siapa mereka.
Ketika anak-anak berlatih menyanyikan lagu kebangsaan, atau mewarnai bendera dengan tangan mungilnya, mereka sedang merawat mawar—menyirami akar rasa bangga yang suatu hari akan mengokohkan mereka. Dan saat mereka berlari di lapangan, tertawa dalam lomba estafet, atau saling memeluk setelah kalah, mereka sedang belajar mencintai negeri ini, tanpa mereka sadari.
Maka, di balik semua kemeriahan Agustus, mungkin inilah yang paling penting: memberi anak-anak ruang untuk jatuh cinta pada Indonesia dengan cara mereka sendiri. Tidak selalu melalui kata-kata besar, tetapi lewat langkah kecil, tawa yang tulus, dan cerita yang kelak akan mereka kenang ketika bendera kembali dikibarkan. Karena pada akhirnya, negeri ini akan menjadi istimewa bagi mereka—bukan karena ia sempurna, tetapi karena mereka telah menghabiskan masa kecil mereka untuk merawatnya, setetes demi setetes, seperti merawat mawar.
RIWAYAT PENULIS
Umi Khomsiyatun adalah seorang pendidik dan peneliti yang memiliki minat dalam bidang literasi membaca, pendidikan dasar, dan Bahasa–sastra dan pembelajaran. Karya-karyanya telah dipresentasikan dalam seminar nasional maupun internasional, serta dipublikasikan di jurnal ilmiah.