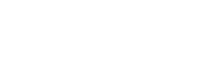Oleh: Abdul Wachid B.S. [1]
Pengantar: Posisi Esai
Ensiklopedi Sastra Nusantara merupakan sebuah ikhtiar kebudayaan yang patut dihargai sebagai kerja kolektif yang tidak ringan. Ia lahir dari kesadaran bahwa sastra-sastra yang tumbuh di berbagai wilayah Nusantara tidak cukup hanya hidup dalam ruang komunitasnya masing-masing, tetapi juga perlu dicatat dan dihadirkan dalam peta pengetahuan yang lebih luas. Dalam pengertian itu, ensiklopedi ini bukan sekadar kumpulan entri, melainkan penanda tanggung jawab intelektual dan kultural: sebuah upaya merawat ingatan sastra agar tidak tercerabut dari sejarahnya.
Sebagai proyek pendataan, ensiklopedi memiliki fungsi yang jelas dan strategis. Ia menyediakan informasi dasar, membuka akses awal, serta memberi legitimasi akademik terhadap tokoh, karya, dan tradisi sastra yang selama ini sering berada di pinggiran wacana sastra nasional. Tanpa kerja semacam ini, banyak jejak sastra lokal berisiko hilang atau hanya bertahan sebagai ingatan lisan yang rapuh. Pada titik inilah apresiasi terhadap proyek Ensiklopedi Sastra Nusantara menjadi penting untuk ditegaskan sejak awal.
Esai ini tidak dimaksudkan sebagai evaluasi teknis atas penyusunan ensiklopedi, baik dari segi metodologi, kelengkapan data, maupun strategi editorial. Posisi tulisan ini lebih tepat dipahami sebagai kontribusi pemaknaan yang berangkat dari pengalaman membaca beberapa entri di dalamnya. Dengan kata lain, perhatian utama esai ini bukan terletak pada bagaimana entri disusun, melainkan pada bagaimana sastra yang telah diringkas dan dipadatkan ke dalam bentuk entri, masih dapat dibaca, dipahami, dan dimaknai.
Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan sastra, baik sebagai pembaca, pengajar, maupun penulis, sastra tidak pernah hadir semata-mata sebagai objek pengetahuan. Ia selalu membawa pandangan hidup, jejak sejarah batin, serta cara manusia memahami relasinya dengan sesama, dengan alam, dan dengan Yang Ilahi. Karena itu, ketika sastra hadir dalam format ensiklopedi, saya cenderung memandangnya sebagai pintu masuk awal, bukan sebagai titik akhir pemahaman. Entri menyediakan arah, tetapi makna sastra tetap lahir melalui pembacaan yang berkelanjutan.
Catatan reflektif ini disusun dalam semangat dialog dan keterbukaan intelektual. Ia tidak dimaksudkan untuk menutup makna sastra dalam rumusan-rumusan tetap, melainkan justru membuka ruang pembacaan yang lebih jernih dan berlapis. Dengan cara demikian, ensiklopedi dapat dipahami bukan hanya sebagai himpunan informasi, tetapi juga sebagai undangan awal untuk terus membaca, menafsir, dan memaknai sastra Nusantara sebagai teks yang hidup: teks yang menyimpan pengalaman, pandangan hidup, dan hikmah yang senantiasa dapat diperbincangkan kembali.
Entri Ensiklopedi dan Cara Kita Membaca Sastra
Entri ensiklopedi pada dasarnya adalah bentuk pemadatan. Ia merangkum, menyeleksi, dan menyusun informasi agar pembaca memperoleh gambaran awal tentang tokoh, karya, atau tradisi sastra tertentu. Dalam konteks ini, entri bekerja sebagai pintu masuk: ia memperkenalkan, memberi arah, dan menuntun pembaca pada wilayah yang lebih luas. Fungsi semacam ini penting, terutama bagi pembaca yang baru pertama kali berjumpa dengan suatu tradisi sastra atau nama pengarang.
Namun, sastra tidak pernah sepenuhnya bisa dipadatkan tanpa menyisakan sesuatu. Ketika sebuah karya, tradisi, atau sosok pengarang diringkas ke dalam entri, yang tampil ke permukaan biasanya adalah informasi yang dapat dicatat secara objektif: latar sejarah, periode, bentuk karya, atau aktivitas kesastraan. Informasi-informasi ini perlu dan berguna, tetapi ia baru menyentuh lapisan luar sastra. Denyut batin, pengalaman estetik, dan pandangan hidup yang menghidupi teks sering kali justru berada di wilayah yang tidak mudah dirumuskan secara ringkas.
Di titik inilah perbedaan antara pendataan sastra dan pemaknaan sastra menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Pendataan berurusan dengan keberadaan: siapa menulis apa, di mana, dan dalam konteks apa. Pemaknaan, sebaliknya, bergerak pada pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana sastra bekerja dalam kehidupan, apa yang ia sampaikan tentang cara manusia memandang dunia, dan mengapa teks tertentu terus dibaca melampaui zamannya. Kedua wilayah ini tidak saling meniadakan, tetapi memiliki logika kerja yang berbeda.
Dalam pengalaman membaca entri-entri ensiklopedi, saya sering merasakan bahwa informasi yang disajikan justru mengundang pembacaan lanjutan. Entri yang baik tidak menutup rasa ingin tahu, melainkan memantik pertanyaan baru. Ia membuat pembaca ingin mencari teksnya, mendengar kembali tradisinya, atau membaca karya-karya lain dari pengarang yang sama. Dengan demikian, entri bukan akhir dari pemahaman, melainkan awal dari proses membaca yang sesungguhnya.
Cara kita membaca ensiklopedi, karena itu, menjadi penting. Jika ensiklopedi diperlakukan sebagai tujuan akhir, sastra berisiko berhenti sebagai pengetahuan yang selesai. Tetapi jika ensiklopedi dibaca sebagai pintu, sastra tetap hidup sebagai pengalaman yang terus bergerak. Dalam cara baca yang kedua ini, entri berfungsi sebagai penunjuk arah, sementara makna sastra lahir dari perjumpaan pembaca dengan teks, konteks budaya, dan pengalaman batinnya sendiri.
Pemaknaan sastra, pada akhirnya, tidak sepenuhnya dapat diwakilkan oleh entri apa pun. Ia menuntut keterlibatan pembaca: kesediaan untuk membaca pelan, mendengarkan suara tradisi, dan membuka diri pada lapisan-lapisan makna yang tidak selalu tampak di permukaan. Ensiklopedi menyediakan peta awal, tetapi perjalanan membaca sastra tetap harus ditempuh oleh pembaca itu sendiri. Di sanalah sastra menemukan kehidupannya yang sesungguhnya; bukan sebagai data yang selesai, melainkan sebagai pengalaman yang terus tumbuh.
Sastra Nusantara sebagai Teks Hidup
Salah satu risiko ketika sastra dicatat, didata, dan diringkas ke dalam format ensiklopedi adalah kecenderungan untuk memperlakukannya sebagai artefak budaya: sesuatu yang selesai, beku, dan dapat disimpan rapi dalam lemari pengetahuan. Padahal, dalam pengalaman saya bersentuhan dengan sastra Nusantara, baik sastra lisan maupun tulisan, sastra tidak pernah hadir sebagai benda mati. Ia selalu hidup, bergerak, dan berdenyut bersama kehidupan masyarakat yang melahirkannya.
Sastra lisan, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari situasi sosial, ritus, dan relasi antarmanusia yang melingkupinya. Pantun, tembang, mantra, atau cerita tutur tidak sekadar disampaikan untuk didengar, tetapi untuk dihadiri. Ia diucapkan pada waktu tertentu, dalam suasana tertentu, dan sering kali oleh orang-orang yang memiliki otoritas kultural dan spiritual di dalam komunitasnya. Dalam konteks ini, sastra bukan hanya teks, melainkan peristiwa. Ia hidup di antara suara, tubuh, ingatan, dan keyakinan bersama.
Hal yang sama, meskipun dalam cara berbeda, juga berlaku pada sastra tulis. Naskah, wawacan, hikayat, atau puisi modern tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil pergulatan batin pengarangnya dengan realitas sosial, tradisi budaya, dan pandangan hidup yang diyakini. Membaca sastra Nusantara sebagai teks hidup berarti menyadari bahwa setiap karya menyimpan lapisan pengalaman manusia yang tidak selalu tampak di permukaan bahasa. Di balik struktur cerita atau keindahan diksi, terdapat cara pandang tentang hidup, tentang penderitaan, tentang harapan, dan tentang makna keberadaan manusia.
Dalam banyak karya sastra Nusantara, kita dapat merasakan kehadiran kosmologi yang khas. Alam tidak diposisikan sebagai objek semata, melainkan sebagai mitra hidup manusia. Gunung, sungai, hutan, dan laut sering hadir bukan sekadar latar, tetapi sebagai entitas yang memiliki makna simbolik dan spiritual. Relasi manusia dengan alam ini membentuk etika hidup yang halus: tentang keseimbangan, tentang batas, dan tentang tanggung jawab. Sastra, dalam hal ini, menjadi medium pewarisan nilai yang tidak selalu diajarkan secara normatif, tetapi dihayati melalui cerita, simbol, dan peristiwa.
Selain kosmologi, sastra Nusantara juga menyimpan apa yang dapat disebut sebagai sejarah batin. Ia merekam cara masyarakat memahami luka, kehilangan, penantian, dan pengorbanan. Sejarah ini tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi atau buku sejarah, tetapi hidup dalam kisah-kisah yang diwariskan lintas generasi. Ketika sebuah cerita rakyat bertahan ratusan tahun, sesungguhnya yang bertahan bukan hanya alurnya, melainkan hikmah yang dianggap relevan oleh para pendengarnya dari zaman ke zaman.
Dalam konteks ini, ensiklopedi memiliki peran penting sebagai penanda keberadaan teks-teks tersebut. Namun, pemaknaan terhadap sastra sebagai teks hidup menuntut kesadaran bahwa entri hanyalah lapisan awal dari perjalanan memahami sastra. Entri mencatat, tetapi kehidupan sastra justru berlanjut ketika pembaca mulai bertanya: mengapa kisah ini diwariskan, nilai apa yang dijaga, dan pandangan hidup apa yang hendak disampaikan melalui simbol-simbolnya.
Pengalaman saya membaca dan mengajarkan sastra menunjukkan bahwa hikmah sastra Nusantara sering kali tidak hadir dalam bentuk pernyataan langsung. Ia tersembunyi dalam alur yang berliku, dalam tokoh yang memilih diam, atau dalam peristiwa yang tampak sederhana. Justru di situlah kekuatan sastra bekerja: mengajak pembaca untuk merenung, bukan untuk segera menyimpulkan. Sastra mengasah kepekaan, bukan memberi jawaban instan.
Karena itu, ketika sastra Nusantara dipahami sebagai teks hidup, kita diajak untuk memperlakukannya dengan sikap rendah hati. Kita tidak datang sebagai penakluk makna, melainkan sebagai peziarah yang bersedia berjalan pelan. Setiap pembacaan adalah perjumpaan baru, karena teks yang hidup akan selalu berbicara berbeda kepada pembaca yang berbeda, dan bahkan kepada pembaca yang sama pada waktu yang berbeda.
Kesadaran inilah yang, menurut saya, perlu terus menyertai kerja-kerja pendataan sastra. Ensiklopedi mencatat jejaknya, tetapi kehidupan sastra itu sendiri berlangsung dalam proses pembacaan, penghayatan, dan dialog yang terus-menerus. Dengan cara pandang demikian, sastra Nusantara tidak direduksi menjadi artefak budaya, melainkan dihadirkan sebagai ruang hidup tempat kosmologi, sejarah batin, dan hikmah manusia Nusantara terus bernafas dan bertransformasi bersama zaman.
Tradisi Lokal (Sunda dan Jawa) dan Dimensi Hikmah
Tradisi sastra lokal di Nusantara pada dasarnya tumbuh dari kebutuhan manusia untuk memahami hidupnya sendiri. Ia tidak lahir terutama sebagai ekspresi estetika yang otonom, melainkan sebagai cara membaca realitas, merawat keseimbangan batin, dan menjaga hubungan dengan alam serta Yang Transenden. Dalam konteks ini, sastra Sunda maupun sastra Jawa dapat dibaca sebagai dua tradisi besar yang memperlihatkan bagaimana sastra bekerja sebagai medium hikmah, bukan sekadar hiburan atau arsip budaya.
Dalam tradisi Sunda, tembang, pantun, wawacan, dan mantra tidak berdiri sebagai teks yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam ritme hidup masyarakat: dinyanyikan, dilagukan, atau diucapkan dalam situasi tertentu yang sarat makna. Bahasa yang digunakan sering tampak sederhana, bahkan kadang repetitif, tetapi di balik kesederhanaan itu tersimpan pandangan hidup yang halus. Keselarasan, kehati-hatian, dan kesadaran akan batas diri menjadi nilai yang terus-menerus dihadirkan, bukan diajarkan secara menggurui, melainkan diresapkan melalui irama dan simbol.
Wawacan, misalnya, bukan hanya kisah panjang yang disusun dalam bentuk pupuh, tetapi juga cara masyarakat Sunda memahami perjalanan hidup manusia. Pergantian pupuh bukan sekadar teknik estetika, melainkan penanda perubahan suasana batin, fase kehidupan, dan ujian moral yang harus dilalui tokoh-tokohnya. Dalam pembacaan yang demikian, sastra menjadi cermin pengalaman batin kolektif, tempat nilai-nilai hidup diwariskan secara perlahan dan berulang.
Hal serupa dapat ditemukan dalam tradisi sastra Jawa. Tembang macapat, serat, maupun kisah-kisah wayang tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi seni, tetapi sebagai peta batin manusia. Setiap tembang macapat, dengan watak dan suasana yang khas, merepresentasikan tahap-tahap kehidupan manusia, dari kelahiran, pertumbuhan, pergulatan, hingga kematian. Sastra, dalam hal ini, menjadi semacam penuntun batin yang membantu manusia membaca dirinya sendiri dalam perjalanan waktu.
Dalam sastra Jawa, konsep tentang laku, tirakat, dan pengendalian diri kerap hadir secara implisit melalui tokoh dan alur cerita. Tokoh-tokoh tidak selalu digambarkan sebagai pahlawan yang menang secara lahiriah, tetapi sebagai manusia yang belajar menerima, mengalah, dan memahami makna di balik peristiwa. Sikap batin semacam ini menunjukkan bahwa sastra bekerja di wilayah yang lebih dalam daripada sekadar narasi peristiwa; ia menyentuh wilayah etika dan spiritualitas.
Baik dalam tradisi Sunda maupun Jawa, mantra memiliki posisi yang khas. Mantra tidak semata-mata dipahami sebagai rangkaian kata bertuah, melainkan sebagai bentuk kesadaran bahasa. Kata-kata dipilih, disusun, dan diucapkan dengan keyakinan bahwa bahasa memiliki daya untuk menata hubungan manusia dengan semesta. Dalam mantra, bahasa tidak hanya menyampaikan makna, tetapi menghadirkan kehadiran. Di sinilah sastra memperlihatkan wajahnya yang paling purba sekaligus paling intim.
Menyandingkan sastra Sunda dan Jawa dalam pembahasan ini bukan untuk menegaskan batas-batas identitas, melainkan untuk menunjukkan keserupaan cara pandang. Keduanya memperlihatkan bahwa sastra lokal Nusantara tumbuh dari kesadaran hikmah: kesadaran bahwa hidup perlu dibaca dengan kepekaan, dijalani dengan keseimbangan, dan dimaknai dengan kerendahan hati. Perbedaan bentuk dan bahasa justru memperkaya cara kita memahami bahwa sastra Nusantara memiliki banyak jalan untuk sampai pada kebijaksanaan.
Dalam konteks ensiklopedi, tradisi-tradisi ini tentu perlu dicatat dan diperkenalkan. Namun, pembacaan yang berorientasi pada hikmah mengingatkan kita bahwa nilai utama sastra lokal tidak berhenti pada informasi tentang bentuk, jenis, atau sejarahnya. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa teks-teks tersebut mengandung cara hidup: cara manusia Nusantara membaca dunia, menata batin, dan menjaga relasinya dengan yang lain.
Dengan demikian, sastra Sunda dan Jawa dapat dipahami sebagai contoh bagaimana tradisi lokal Nusantara menjadikan sastra sebagai jalan permenungan. Ia tidak memaksa pembaca untuk segera memahami, tetapi mengajak untuk pelan-pelan menghayati. Di sanalah hikmah bekerja: tidak sebagai rumus yang selesai, melainkan sebagai proses yang terus hidup bersama pembacanya.
Tawaran Cara Memperkaya Entri Ensiklopedi
Berangkat dari pembacaan terhadap ensiklopedi sebagai pintu masuk, bukan sebagai simpulan akhir, ada beberapa kemungkinan pengayaan yang dapat dipertimbangkan tanpa mengubah watak dasar ensiklopedi itu sendiri. Yang saya maksudkan di sini bukanlah revisi dalam pengertian teknis, melainkan perluasan sudut pandang agar entri-entri yang ada dapat semakin membuka ruang pemaknaan bagi pembacanya.
- Pertama, pengayaan perspektif pembacaan.
Entri ensiklopedi pada dasarnya menyajikan informasi faktual yang ringkas dan padat. Namun, sastra tidak hanya hidup dalam fakta, melainkan juga dalam cara ia dibaca. Pengayaan perspektif dapat dilakukan dengan memberi isyarat, meski sangat singkat, tentang kemungkinan pembacaan yang lebih luas: apakah sebuah karya lahir dari tradisi lisan, dari pengalaman spiritual, dari situasi sosial tertentu, atau dari pergulatan batin pengarangnya. Isyarat semacam ini tidak dimaksudkan untuk menafsirkan secara tuntas, tetapi untuk mengarahkan pembaca agar menyadari bahwa teks sastra selalu membuka lebih dari satu pintu makna.
- Kedua, penambahan lapis makna kultural dan batiniah.
Banyak karya sastra Nusantara mengandung lapisan makna yang tidak selalu tampak dalam ringkasan isi atau keterangan bentuk. Di balik alur cerita, pilihan pupuh, atau struktur bahasa, sering tersimpan nilai, etos hidup, dan cara pandang terhadap dunia. Menyebutkan secara singkat lapisan ini, misalnya sebagai catatan konteks kultural atau orientasi nilai, dapat membantu pembaca memahami bahwa sastra tidak hanya bercerita tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana manusia memaknai kehidupannya. Lapis makna ini tidak perlu dirumuskan secara teoritis, cukup dihadirkan sebagai kesadaran.
- Ketiga, kesadaran terhadap simbol dan visi hidup tradisi atau pengarang.
Sastra Nusantara kaya dengan simbol yang berakar pada pengalaman kolektif: alam, perjalanan, pengorbanan, kesetiaan, atau penyerahan diri. Simbol-simbol ini bukan ornamen estetika semata, melainkan cara suatu tradisi atau pengarang menata pandangan hidupnya. Entri ensiklopedi, tanpa harus menjadi ruang tafsir panjang, dapat memperlihatkan kepekaan terhadap simbol-simbol kunci yang sering muncul dalam suatu tradisi atau karya. Dengan cara itu, ensiklopedi tidak hanya mencatat apa yang ada, tetapi juga mengisyaratkan visi hidup yang melandasinya.
Ketiga tawaran ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ensiklopedi menjadi buku tafsir sastra. Sebaliknya, ia justru menjaga ensiklopedi tetap pada fungsinya sebagai rujukan awal, sambil memberi ruang bagi pembaca untuk melangkah lebih jauh. Dengan pengayaan semacam ini, entri ensiklopedi dapat berfungsi ganda: sebagai sumber informasi dan sebagai undangan halus untuk membaca sastra Nusantara dengan kesadaran yang lebih dalam dan manusiawi.
Penutup
Di tengah derasnya arus informasi dan percepatan zaman, penulisan Ensiklopedi Sastra Nusantara menjadi penting bukan semata-mata karena kebutuhan akademik, melainkan karena ia berangkat dari kesadaran kebudayaan yang lebih dalam: bahwa sastra-sastra yang hidup di Nusantara perlu dirawat sebagai bagian dari pengalaman manusia yang panjang dan berlapis. Ensiklopedi ini hadir sebagai ikhtiar untuk menata ingatan, agar keragaman sastra tidak tercerai-berai dalam fragmen yang terpisah, melainkan dapat dibaca sebagai lanskap bersama yang memperlihatkan kekayaan pandangan hidup, nilai, dan hikmah yang tumbuh dari berbagai tradisi.
Ensiklopedi, pada akhirnya, selalu bersifat terbuka. Ia tidak pernah benar-benar selesai, sebab yang dicatat di dalamnya adalah kehidupan yang terus bergerak. Sastra Nusantara, dengan segala ragam bahasa, bentuk, dan tradisinya, tidak berhenti tumbuh hanya karena telah diringkas dalam entri-entri yang rapi. Justru di situlah tantangannya: bagaimana ensiklopedi dapat menjadi ruang temu awal antara pengetahuan dan pengalaman, antara data dan kesadaran, antara arsip dan kehidupan.
Dalam pengertian itu, Ensiklopedi Sastra Nusantara dapat dibaca sebagai arsip yang hidup. Ia menyimpan jejak-jejak sastra, tetapi tidak memenjarakannya. Ia mencatat keberadaan, tanpa mengklaim pemaknaan tunggal. Pembaca yang datang dengan keingintahuan akan menemukan pintu-pintu awal, sementara makna sesungguhnya menunggu untuk digali melalui pembacaan yang sabar, dialog yang jujur, dan keterlibatan batin yang sungguh-sungguh.
Harapan saya sederhana, tetapi mendasar: agar ensiklopedi ini tidak hanya berfungsi sebagai rujukan akademik, melainkan juga sebagai suluh kebudayaan. Suluh yang menerangi jalan bagi generasi pembaca berikutnya untuk mengenali, mencintai, dan merawat sastra Nusantara bukan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai sumber hikmah yang tetap relevan bagi kehidupan hari ini. Sastra, pada akhirnya, tidak hidup untuk dikenang semata, melainkan untuk terus dibaca ulang, dimaknai ulang, dan dihidupi dalam kesadaran zaman yang terus berubah.
Jika ensiklopedi ini kelak mampu menumbuhkan keinginan untuk membaca lebih jauh, mendengar lebih dalam, dan memahami dengan lebih rendah hati, maka ikhtiar kebudayaan yang melahirkannya telah menemukan maknanya. Di sanalah sastra Nusantara tidak hanya tercatat, tetapi sungguh-sungguh hadir: sebagai teks hidup yang terus menyapa manusia dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang suatu peradaban.***
[1] Penulis adalah penyair, Ketua Sekolah Kepenulisan Sastra Pedaban (SKSP) dan Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
Abdul Wachid B.S. lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Mengajar di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Buku-buku puisinya, antara lain, Biyanglala (Cinta Buku, 2020), Jalan Malam (Basabasi, 2021), Penyair Cinta (Jejak Pustaka, 2022). Buku esainya Sastra Pencerahan (Basabasi, 2019) menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) pada 2021.