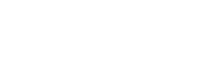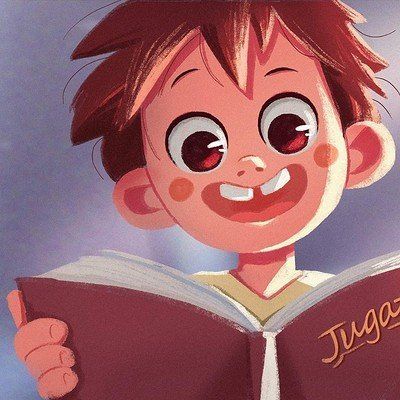Apakah kamu masih ingat kapan terakhir kali membaca cerita anak? Mungkin dongeng sebelum tidur, komik ringan, atau fabel yang dibacakan guru di sekolah dasar. Meski terlihat sederhana, sebenarnya ada dunia yang kaya di balik bahasa sastra anak. Bahasa dalam karya-karya itu bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan yang menuntun anak mengenal dunia, memahami perasaan, dan menumbuhkan imajinasi.
Sastra anak pada dasarnya adalah sastra yang ditujukan untuk anak, dilihat dari sudut pandang anak, ditulis dengan gaya bahasa ala anak, bahkan kadang-kadang ditulis oleh anak. Karena itu, karakter bahasa menjadi hal penting yang menentukan apakah sebuah cerita bisa dicerna dan dinikmati oleh pembaca cilik.
Menurut Riris K. Toha Sarumpaet, bahasa cerita anak umumnya berbentuk kalimat-kalimat sederhana, struktur gramatikalnya mudah, dan pemilihan diksi disesuaikan dengan tahap pemerolehan bahasa anak. Rumidjan menambahkan bahwa karakter sastra anak bisa dilihat dari sisi kebahasaan dan kesastraan. Dari segi kebahasaan, kalimat yang dipakai biasanya tunggal dan jelas: kalimat berita, tanya, atau perintah sederhana. Pilihan katanya adalah kosakata yang sudah akrab di telinga anak, sementara gaya bahasa kiasan (majas) digunakan secara terbatas agar tidak membingungkan.
Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kesederhanaan bahasa” itu? Jawabannya bisa ditelusuri lewat tahapan perkembangan bahasa anak. Sutanto membaginya ke dalam beberapa fase: mulai dari tahap pra-linguistik (0–1 tahun) ketika bayi hanya meniru bunyi sederhana, tahap linguistik (0–2 tahun) saat anak menguasai 50–100 kosakata, tahap tata bahasa sederhana (3–5 tahun) ketika anak mampu membuat kalimat dasar, hingga tahap pemerkaya (8–15 tahun) ketika kemampuan bahasa mereka hampir setara dengan orang dewasa meski kosakatanya lebih terbatas.
Hal ini sejalan dengan pandangan Hendra Sofyan yang menekankan perkembangan kosakata, semantik, sintaksis, serta variasi bahasa. Anak-anak belajar dari lingkungan: dari cara guru berbicara, dari orang tua bercerita, atau bahkan dari dialog sederhana di televisi. Mereka belajar menyusun kalimat dengan benar (“Adik minum susu”, bukan “Minum adik susu”), memahami makna kata, serta perlahan mengenal sinonim, kata ganti, bentuk pasif, hingga struktur kalimat yang lebih kompleks.
Itu sebabnya, menyusun bahasa untuk sastra anak bukan perkara mudah. Kalimat yang terlalu panjang bisa membuat anak kehilangan arah. Sebaliknya, kalimat sederhana, meski singkat, dapat lebih efektif menyampaikan makna. Contohnya, kalimat rumit seperti “Adik menyukai permen rasa coklat yang dibeli oleh ibu di warung seberang rumah nenek” bisa dipecah menjadi beberapa kalimat pendek: “Adik suka permen coklat. Ibu yang membeli permen itu. Warungnya ada di seberang rumah nenek.” Dengan begitu, pesan cerita tetap utuh, tetapi lebih mudah dipahami.
Lalu, apakah itu berarti bahasa sastra anak harus selalu lugas dan bebas dari majas? Tidak juga. Justru di sinilah menariknya. Anak-anak juga berhak merasakan indahnya bahasa yang berlapis, asal disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Di sinilah peran stilistika—ilmu yang mengkaji variasi penggunaan bahasa dalam karya sastra. Stilistika menjadi jembatan antara linguistik dan kritik sastra, membantu kita memahami bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa dapat memengaruhi daya tarik sebuah cerita.
Lakoff dan Johnson dalam Metaphors We Live By mengingatkan kita bahwa manusia hidup dikelilingi metafora. Kita tidak pernah benar-benar lepas dari bahasa kiasan, bahkan dalam percakapan sehari-hari: jatuh cinta, patah hati, keras kepala, ujian di ambang pintu, gantungkan cita-cita setinggi langit. Ungkapan semacam itu menunjukkan betapa metafora melekat dalam cara kita berpikir.
Karena itu, memperkenalkan metafora sederhana pada anak bisa menjadi bagian dari pembelajaran bahasa dan sastra. Misalnya, seorang tokoh digambarkan sebagai “tulang punggung keluarga”, ungkapan yang mungkin butuh sedikit penjelasan, tetapi justru melatih anak memahami bahwa bahasa tidak selalu hitam putih.
Pada akhirnya, bahasa dalam sastra anak adalah bahasa yang sederhana tapi tidak miskin makna. Ia ramah, akrab, dan sesuai tahap perkembangan pembaca, tetapi tetap bisa memuat keindahan stilistika maupun kekuatan metafora. Sastra anak tidak sekadar hiburan, tetapi juga alat pendidikan emosional dan linguistik.
Maka, pertanyaannya kembali pada kita: kapan terakhir kali membaca atau membacakan cerita anak? Mungkin sudah saatnya kita kembali membuka buku dongeng, menelusuri kembali kesederhanaan bahasa yang justru menyimpan kedalaman. Karena lewat bahasa dalam sastra anak, kita belajar bahwa kesederhanaan tidak berarti keterbatasan, melainkan justru pintu menuju kekayaan imajinasi dan kebijaksanaan hidup.