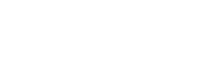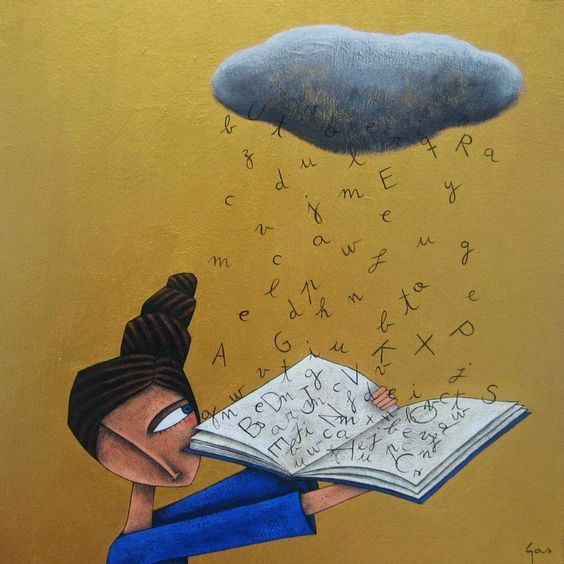Ketika Sastra Kehilangan Ruhnya di Kelas
Di ruang kelas hari ini, sastra tampaknya hidup. Buku kumpulan puisi, cerpen, hingga novel tersedia. Guru meminta siswa mencatat alur cerita, menandai tokoh, menjawab soal tentang amanat dan sudut pandang. Di atas kertas, semua itu tampak seperti wujud dari pembelajaran literasi sastra. Namun benarkah semua itu pertanda bahwa literasi sastra benar-benar tumbuh?
Sayangnya, pembelajaran sastra di sekolah kerap menyempit menjadi sekadar alat mencapai nilai akademik. Karya-karya sastrawan besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Nh. Dini, atau Sapardi Djoko Damono hanya dibaca untuk dicatat struktur ceritanya, bukan untuk direnungi hikmah dan kehalusan rasa yang dikandungnya. Puisi hanya dibedah majas, bukan untuk dihayati maknanya. Novel diperlakukan sebagai objek ringkasan, bukan pengalaman batin yang mengubah cara pandang. Akibatnya, sastra kehilangan daya hidupnya di benak siswa. Ia berubah menjadi hafalan tanpa ruh.
Kondisi ini menimbulkan ironi besar. Di satu sisi, kurikulum mewajibkan siswa mengenal sastra. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan justru menjauhkan siswa dari pengalaman sastra yang sejati. Sastra bukan lagi jendela empati dan rasa, melainkan sebatas beban soal dan hafalan istilah. Padahal, literasi sastra sejatinya bukan hanya kemampuan memahami isi teks, melainkan kemampuan merasakan, merenungkan, dan mengolah nilai-nilai kemanusiaan yang tersirat di dalamnya (Rosenblatt, Literature as Exploration, New York: Modern Language Association, 1995:25).
Lebih memprihatinkan lagi, buku-buku sastra kini harus bersaing dengan layar gawai dan alur cepat media digital. Di era serba visual dan instan, perhatian siswa lebih tersita pada konten-konten pendek: TikTok, sinetron remaja, drama Korea, meme, dan video-video singkat lainnya. Cerita yang panjang dan reflektif kerap dianggap membosankan. Banyak siswa bahkan lebih memilih mencari “sinopsis” atau “analisis unsur intrinsik” di internet ketimbang membaca karya aslinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita belum berhasil menumbuhkan cinta membaca, khususnya karya sastra.
Mengembalikan Sastra sebagai Pengalaman Hidup
Padahal, dalam puisi tersimpan keheningan dan perenungan. Dalam cerpen, terhampar ragam hidup manusia dengan segala luka dan harapnya. Dalam novel, terbentang perjalanan nilai, ideologi, dan pertumbuhan batin. Sastra adalah medan pembentukan kepekaan dan pendewasaan jiwa. Membaca sastra adalah mengalami perjalanan batin orang lain tanpa harus menanggung resiko langsung dari pengalaman itu.
Pertanyaannya: apakah semua kekayaan itu masih mungkin dialami di ruang kelas hari ini? Jawabannya: sangat mungkin. Asalkan pendekatannya diubah. Sastra harus kembali dihadirkan sebagai pengalaman, bukan sebagai objek hafalan. Guru seharusnya menjadi fasilitator dialog antara teks dan kehidupan. Siswa tidak cukup hanya mencari tema cerita, tetapi juga diajak berdiskusi, menulis surat kepada tokoh fiktif, membayangkan ulang akhir cerita, atau menafsirkan puisi berdasarkan pengalaman personal mereka.
Sebagai contoh, ketika siswa membaca “Robohnya Surau Kami” karya A.A. Navis, tujuan pembacaan tidak cukup berhenti pada pencatatan alur atau identifikasi tokoh. Lebih dari itu, siswa perlu diajak merenung: mengapa tokoh Haji Saleh merasa hidupnya sia-sia? Apakah amal ibadah cukup tanpa kepedulian sosial? Bagaimana kita menyikapi persoalan agama dalam relasi dengan kehidupan nyata? Dari situ, sastra menjadi sarana berpikir, bercermin, dan bertumbuh.
Pendekatan ini selaras dengan konsep reader-response yang dikembangkan Louise M. Rosenblatt, di mana makna sebuah karya sastra terbentuk melalui interaksi aktif antara teks dan pembaca. Rosenblatt menegaskan, “The poem exists in the transaction between the reader and the text” (Puisi hadir dalam transaksi antara pembaca dan teks) (The Reader, the Text, the Poem, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1978: 14).
Dari Kewajiban ke Kebutuhan Jiwa
Kurikulum Merdeka sejatinya memberi ruang luas untuk pendekatan semacam ini. Sayangnya, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Banyak guru belum memiliki keberanian atau kreativitas untuk menafsirkan ulang cara mengajar sastra secara humanistik. Padahal, guru yang membaca puisi dengan penuh rasa, atau bercerita seperti mendongeng, sering kali membuat siswa jatuh cinta pada sastra. Bagi sebagian siswa, pengalaman itulah yang menjadi pintu masuk menuju dunia buku.
Peningkatan kapasitas guru sastra menjadi mutlak. Pelatihan yang mengedepankan metode kreatif, berbasis proyek, partisipatif, dan reflektif harus diperluas. Sekolah perlu memperbanyak akses terhadap bacaan sastra yang relevan—tidak hanya karya klasik, tetapi juga karya kontemporer yang berbicara dengan bahasa generasi muda. Pengalaman literasi harus dipersonalisasi, sehingga siswa merasa “disapa” oleh teks yang mereka baca.
Kolaborasi dengan komunitas sastra, penulis, atau lembaga literasi juga dapat menjadi jembatan penting. Siswa bisa mengikuti kelas menulis kreatif, pementasan drama, lomba baca puisi, atau diskusi buku. Aktivitas ini menunjukkan bahwa sastra bukan sekadar pelajaran di sekolah, tetapi bagian dari kehidupan. Kegiatan seperti “Bedah Buku” atau “Poetry Reading” yang menghadirkan sastrawan ke sekolah mampu menyalakan rasa ingin tahu siswa.
Sastra, jika dipahami dan dihayati, menjadi lahan subur pembentukan kepekaan manusia. Ia memperluas empati, memperkaya imajinasi, dan memperhalus rasa. Mengabaikan dimensi ini berarti mengabaikan bagian penting dari pembentukan manusia seutuhnya. Di titik ini, literasi sastra juga berfungsi sebagai penopang peradaban—membentuk masyarakat yang mampu mendengar suara hati sebelum mengambil keputusan.
Menumbuhkan Cinta Membaca di Tengah Tantangan Zaman
Tidak dapat dipungkiri, generasi sekarang hidup di tengah derasnya arus informasi. Kecepatan menjadi nilai utama, sementara kesabaran membaca karya panjang dianggap kuno. Di sinilah tugas literasi sastra menjadi semakin penting: ia harus melatih kesabaran, konsentrasi, dan kemampuan menyelami makna yang tidak instan.
Pengalaman di beberapa sekolah menunjukkan bahwa jika siswa diberi kesempatan memilih bacaan sesuai minat, lalu diberi ruang untuk mengekspresikan tanggapan mereka secara kreatif—entah melalui ilustrasi, video pendek, musikalisasi puisi, atau drama—maka minat mereka pada bacaan akan meningkat. Pendekatan ini menghubungkan sastra dengan dunia mereka, tanpa mengorbankan kedalaman makna.
Selain itu, peran keluarga tidak kalah penting. Orang tua yang membacakan cerita sebelum tidur atau menyediakan waktu khusus untuk membaca bersama telah menanamkan benih kecintaan pada buku sejak dini. Jika benih ini dipelihara oleh sekolah melalui pembelajaran yang hangat dan inspiratif, maka sastra tidak akan lagi menjadi sekadar tugas sekolah, melainkan bagian dari identitas pribadi.
Dari Tugas ke Cinta
Maka, literasi sastra harus dibebaskan dari belenggu soal dan tugas semata. Ia perlu kembali menjadi jalan pembebasan rasa dan makna. Membaca sastra harus menjadi sebuah perjalanan—kadang lambat, kadang mengejutkan—yang membawa kita bertemu diri sendiri dan orang lain dalam ruang batin yang sama.
Jika kita ingin generasi mendatang tumbuh peka, kritis, dan penuh empati, sastra harus ditanamkan bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Literasi sastra harus berpindah dari ruang hafalan ke ruang hati—dari sekadar tugas ke cinta membaca. Sebab pada akhirnya, yang membentuk manusia bukan sekadar pengetahuan yang dihafal, tetapi pengalaman batin yang mengubah cara ia memandang dunia.***