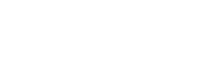Perkembangan anak tidak hanya tumbuh secara fisik tetapi juga berkembang secara sosial dan emosi. Perkembangan sosial dan emosi yang sehat sangatlah penting untuk anak. Hal ini akan menjadikan dirinya mampu bertingkah laku yang pantas, memahami arti hidup, serta mampu melewati masa dari anak – anak hingga dewasa tanpa kendala apapun. Dalam hal ini emosi memainkan peran yang cukup penting dalam bersosialisasi.
Kemampuan interaksi sosial anak merupakan kemampuan untuk bekerja sama dan bermain dengan orang – orang disekitarnya. Mampu memberi perhatian terhadap orang dewasa atau guru serta mampu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Interaksi Sosial pada anak sekolah dasar ditandai dengan adanya hubungan di dalam pembelajaran di kelas maupun saat bermain di luar kelas, disamping dengan keluarga juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas (Haditono, 2006).
Sedangkan Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, bisa berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam World Book Dictionary, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, kesenangan, dan kesedihan. Perasaan semacam ini adalah gambaran emosi. Goleman menyatakan bahwa emosi mengacu pada perasaan atau pikiran yang khas, keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak (Goleman, 1995).
Perkembangan Sosial dan emosi anak merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian karena merupakan dasar untuk membina hubungan atau berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selama ini masih banyak yang mengesampingkan emosi anak yang tanpa disadari ketika emosi terhambat maka akan berpengaruh terhadap perilaku sosial. Anak yang memiliki masalah emosi cenderung memiliki hambatan besar dalam persahabatan, penyesuaian sosial, perilaku, akademik serta anak secara sosial tersisih, pemalu, kesepian dan terisolasi penarikan diri (Rini Hildayani, 2011). Dari sinilah, itu salah satu kemampuan yang perlu dimiliki untuk mendukung terciptanya hubungan atau interaksi sosial yang baik adalah literasi emosi.
Literasi emosi dapat memperbaiki relasi dan menciptakan kasih sayang antar orang dan bekerjasama serta memfasilitasi penumbuhan perasaan saudara sebagai suatu komunitas (feeling of communtity). Seperti yang dijelaskan oleh Sharp (2001) yang menyatakan bahwa literasi emosi merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, manangani dan mengekspresikan emosi dengan tepat.
Mengidentifikasi Interaksi Sosial
Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain atau disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik (Hurlock, 1990).
Menurut Fatnar (2014) kemampuan interaksi sosial merupakan suatu kesanggupan individu untuk saling berhubungan dan bekerja sama dengan individu lain maupun kelompok di mana satu sama lain dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki. Sehingga hal itu dapat memunculkan suatu hubungan timbal balik. Menurut Maryati & Suryawati (2001:56) interaksi sosial adalah “hubungan timbal balik (sosial) berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok”. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, siswa tidak lepas dari berhubungan sosial dengan orang lain. Hal ini karena setiap hari siswa melakukan interaksi dengan individu baik secara langsung atau tatap muka maupun secara tidak langsung. Interaksi sosial erat hubungannya dengan emosi.
Perkembangan Sosial Emosional Anak
Perkembangan sosial emosional anak adalah proses dimana anak belajar memahami perasaan diri sendiri, mengendalikan emosi, menjalin hubungan dengan orang lain, serta berperilaku sesuai norma sosial. Perkembangan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk karakter, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan. Menurut Erik Erikson dalam teori Psikososial, anak usia dini berada pada tahap initiative vs guilt (inisiatif vs rasa bersalah), di mana mereka mulai ingin mencoba hal baru, berinteraksi, dan membangun rasa percaya diri. Jika perkembangan ini tidak terfasilitasi dengan baik, anak bisa tumbuh menjadi pemalu dan kurang percaya diri.
Vygotsky melalui teori sosiokultural menekankan bahwa perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang dewasa maupun teman sebaya. Anak belajar nilai, norma, dan keterampilan sosial melalui proses scaffolding atau bimbingan dari orang lain. Misalnya, anak yang diajari berbagi mainan oleh orang tua atau guru akan belajar bahwa berbagi membuat hubungan sosial menjadi lebih baik. Dengan kata lain, lingkungan sekitar sangat menentukan kualitas perkembangan sosial emosional anak.
Contoh nyata perkembangan sosial emosional dapat terlihat pada anak usia prasekolah yang mulai belajar bekerja sama dalam permainan kelompok. Misalnya, ketika bermain balok, anak belajar menunggu giliran, menghargai ide teman, dan menyelesaikan konflik kecil. Dari sisi emosional, anak mulai belajar mengendalikan perasaan seperti marah atau kecewa ketika mainannya diambil teman. Hal ini menunjukkan keterampilan regulasi emosi yang berkembang seiring dengan bimbingan dan contoh dari orang dewasa.
Keterampilan sosial emosional juga memengaruhi kesiapan anak dalam belajar akademik. Anak yang mampu mengendalikan emosi, bekerja sama dengan teman, dan menghormati guru akan lebih mudah mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, anak yang bisa menunggu giliran berbicara di kelas akan lebih diterima oleh teman-temannya dan mendapatkan pengalaman belajar yang positif. Penelitian Denham (2006) menyatakan bahwa perkembangan sosial emosional yang baik berkorelasi dengan keberhasilan akademik dan kesejahteraan psikologis anak.
Untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangatlah penting. Orang tua dapat memberikan teladan dalam mengelola emosi, guru dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif, dan lingkungan dapat menyediakan kesempatan anak bersosialisasi. Misalnya, membiasakan anak mengucapkan salam, bermain peran di kelas, atau berdiskusi ringan tentang perasaan. Dengan dukungan ini, anak akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mampu berempati, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.
Literasi Emosi Anak
Kurangnya pemahaman siswa terhadap emosional pada dirinya, membuat siswa tidak mampu mengendalikan emosinya dan menyesuaikan dirinya dengan situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Siswa yang sulit mengelola emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain dan berhubungan baik dengan orang lain. Untuk mengelola atau mengkontrol emosi dengan baik , tentu harus ada pemahaman serta pengetahuan terhadap emosi tersebut. Salah satu pengetahuan yang mencakup tentang pengelolaan dan pemahaman terhadap emosi adalah literasi emosi.
Literasi emosi digambarkan sebagai kesadaran akan perasaan kita sendiri untuk meningkatkan kekuatan pribadi dan kualitas hidup kita serta kualitas hidup orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dijelaskan oleh Sharp (2001) yang menyatakan bahwa “literasi emosi merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, menangani dan mengekspresikan emosi dengan tepat”. Seseorang disebut melek emosi apabila ia mampu menangani emosi dengan suatu cara yang dapat memperbaiki kualitas diri dan memperbaiki kualitas kehidupan disekitarnya. Literasi emosi dapat memperbaiki relasi dan menciptakan kasih sayang antar orang dan bekerjsama serta memfasilitasi penumbuhan perasaan saudara sebagai suatu komunitas (feeling of communtity).
Dalam dunia sekolah, literasi emosi dicerminkan dalam jenis kegiatan dan tujuan yang diperlukan sekolah dengan titik tekan pada relasi interpersonal yang dicirikan dengan dialog antara peserta didik dan peserta didik, juga peserta didik dan guru (Mathews:2006). Steiner & Perry (1997) menjelaskan bahwa literasi emosi terdiri dari lima aspek, yaitu mengetahui perasaan diri, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk mengakui emosi, kemampuan untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan emosi serta kemampuan untuk lebih memahami dunia dan konteks sosial. Kelima aspek ini merupakan ‘interaktivitas emosi’.
Mereka berpendapat bahwa menjadi sadar & dapat memahami perasaan diri sendiri & orang lain menjadikan interaksi lebih efektif. Literasi emosi merupakan perkembangan kesadaran tentang emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Informasi kesadaran ini yang akan memandu pikiran kita dan diekspresikan dalam komunikasi dan perilaku kita. Perlu dipahami bahwa setiap individu merasakan emosi dalam cara yang berbeda oleh karena itu memiliki respon yang berbeda pula tergantung kepada pengalaman hidup mereka (Parkhead Nursery Staf 2004 dalam Bruce, 2010).
Mengajarkan Keterampilan Sosial Dasar
Mengajarkan keterampilan sosial dasar pada anak merupakan fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan sosial mencakup cara berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, serta menghormati orang lain. Menurut Gresham & Elliott (1990), keterampilan sosial adalah perilaku yang dipelajari untuk memfasilitasi interaksi yang positif dengan lingkungan sosial. Dengan bekal keterampilan ini, anak akan lebih mudah diterima dalam kelompok, terhindar dari konflik berkepanjangan, dan mampu membangun hubungan yang sehat.
Salah satu keterampilan sosial dasar yang perlu diajarkan adalah berkomunikasi dengan baik. Anak belajar mendengarkan orang lain, menunggu giliran bicara, serta mengungkapkan pendapat dengan sopan. Misalnya, guru dapat melatih anak melalui kegiatan diskusi ringan atau bercerita di depan kelas. Anak yang terbiasa menyampaikan pendapat akan tumbuh lebih percaya diri dan mampu menghargai perbedaan pandangan. Hal ini sejalan dengan teori Vygotsky (1978) yang menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan kunci utama perkembangan bahasa dan berpikir anak.
Selain komunikasi, anak juga perlu dilatih keterampilan berbagi dan bekerja sama. Misalnya, saat bermain balok di kelas, anak diajak untuk saling berbagi bahan dan menyusun bangunan secara bersama-sama. Guru atau orang tua dapat memberikan contoh konkret dengan mengatakan, “Kamu bisa memberi sebagian balokmu ke teman, lalu kita bangun bersama.” Kegiatan ini menumbuhkan rasa kebersamaan sekaligus mengurangi perilaku egois. Anak belajar bahwa kerja sama membuat kegiatan lebih menyenangkan dan hasilnya lebih baik.
Keterampilan lain yang penting adalah menyelesaikan konflik secara sehat. Anak usia dini sering mengalami perselisihan, misalnya berebut mainan. Di sinilah orang dewasa berperan sebagai fasilitator untuk mengajarkan cara meminta maaf, bernegosiasi, atau mencari solusi bersama. Contoh: seorang guru menengahi dengan berkata, “Bagaimana kalau mainannya dipakai bergantian selama 5 menit?” Dengan cara ini, anak belajar mengendalikan emosi, menghargai hak orang lain, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.
Mengajarkan keterampilan sosial dasar sebaiknya dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan, seperti permainan peran, storytelling, maupun aktivitas kelompok. Orang tua dan guru perlu menjadi teladan dalam bersikap sopan, ramah, dan saling menghargai. Dengan pembiasaan yang konsisten, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berempati, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi tantangan sosial di masa depan. Seperti dinyatakan oleh Denham & Burton (2003), perkembangan keterampilan sosial sejak dini memiliki dampak jangka panjang terhadap keberhasilan akademik dan kesejahteraan psikologis anak.
Dari sinilah, literasi sosial dan emosional merupakan aspek penting dalam perkembangan anak yang berperan besar terhadap pembentukan karakter, kemampuan beradaptasi, serta keberhasilan akademik dan sosialnya. Melalui literasi sosial, anak belajar cara berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, serta memahami nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, literasi emosi membantu anak mengenali, memahami, dan mengelola perasaan diri sendiri maupun orang lain secara tepat, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Perkembangan sosial dan emosional yang baik tidak terjadi secara alami, melainkan perlu difasilitasi melalui pembelajaran yang terarah dan konsisten, baik di rumah maupun di sekolah. Guru dan orang tua memiliki peran penting sebagai teladan dan fasilitator dalam menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan pengendalian diri anak melalui kegiatan sehari-hari yang bermakna.
Dengan menanamkan literasi sosial dan emosional sejak dini, anak akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, berempati, mampu menyelesaikan konflik dengan bijak, serta siap menghadapi tantangan kehidupan sosial di masa depan. Literasi ini bukan hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga membentuk dasar bagi kesejahteraan psikologis dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
Referensi
- Denham, S. A. (2006). Social emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? Early Education and Development, 17(1), 57–89. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_4
- Denham, S. A., & Burton, R. (2003). Social and Emotional Prevention and Intervention Programming for Preschoolers. Springer.
- Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society (2nd ed.). W. W. Norton & Company.
- Fatnar, A. (2014). Psikologi Sosial: Interaksi dan Hubungan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
- Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1990). Social Skills Rating System. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
- Haditono, S. R. (2006). Psikologi Perkembangan Anak. Yogyakarta: Liberty.
- Hurlock, E. B. (1990). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terj. Istiwidayanti & Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.
- Maryati, K., & Suryawati, J. (2001). Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Erlangga.
- Mathews, G. (2006). Understanding Emotional Literacy in Schools. London: Routledge.
- Rini Hildayani. (2011). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sharp, P. (2001). Nurturing Emotional Literacy: A Practical Guide for Teachers, Parents and Those Working in the Caring Professions. London: David Fulton Publishers.
- Steiner, C., & Perry, P. (1997). Achieving Emotional Literacy: A Personal Program to Increase Your Emotional Intelligence. New York: Bloomsbury Publishing.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.