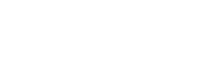Oleh: Mukhamad Hamid Samiaji,
Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan Pemerhati Bahasa di Lembaga Kajian Nusantara Raya UIN Saizu Purwokerto.
“Bahasa adalah elemen paling mendasar bagi perkembangan peradaban manusia”
-Renhad Saupia-
Di Indonesia, penggunaan bahasa dihadapkan dengan beragam bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Secara umum, anak-anak akan mendengar bahasa ibunya terlebih dahulu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari seorang anak dari ibunya. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah (indigenous language) (Linguist, 2023). Bahasa ibu dapat pula berupa bahasa Indonesia. Bagi anak-anak yang dibesarkan di kota-kota besar, bahasa ibunya dapat berupa bahasa Indonesia. Bagi seorang anak yang lahir di luar negeri atau yang salah satu orang tuanya, terutama ibunya, merupakan orang asing, bahasa ibu anak itu adalah bahasa asing, bergantung pada tempat kelahirannya atau bahasa yang digunakan salah seorang orang tuanya. Jadi, bahasa pertama seorang anak merupakan bahasa awal yang dikenalnya (Felicia N. Utorodewo, 2019).
Pengajaran bahasa Indonesia selama ini dilakukan layaknya bahasa pertama bagi anak. Anak dianggap sudah memiliki keterampilan berbahasa dasar dalam bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa diberikan dengan anggapan anak sudah mengetahui cara melafalkan kata dan memahami arti kata dalam bahasa Indonesia. Intonasi juga dianggap sudah dikuasai dan mengabaikan kenyataan bahwa lafal dan intonasi bahasa daerah berbeda dari bahasa Indonesia. Dalam kenyataannya, tidak selalu semudah itu.
Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, kadang-kadang aksaranya, dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Berarti, bahasa diajarkan sebagai bahasa yang sama sekali belum dikenal oleh anak. Semua diajarkan: pelafalan, kosakata, tata bahasa, situasi, bahkan cara menulis pun diajarkan untuk bahasa tertentu, seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, dan sebagainya.
Di Indonesia, situasi kemampuan berbahasa anak-anak bervariasi. Seorang anak dapat disebut sebagai seorang yang monolingual (menguasai satu bahasa); bilingual (menguasai dua bahasa); atau seorang yang poliglot (menguasai lebih dari dua bahasa). Seorang anak yang dibesarkan di daerah perkotaan, ditambah dengan orang tua yang berpendidikan tinggi, akan mampu berbahasa Indonesia dan mungkin bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Seorang anak yang dibesarkan di daerah pinggiran kota, mungkin dengan orang tua yang berpendidikan tinggi, mungkin pula tidak, akan mampu berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia. Seorang anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dan, mungkin, terpencil hanya mampu berbahasa daerah.
Keadaan itu menunjukkan bahwa seorang anak sejak dini mampu menjadi seseorang yang poliglot (menguasai banyak bahasa sekaligus). Tentu, dengan akibat tertentu, misalnya anak akan lamban berbicara. Kelambanan terjadi karena anak sibuk mengingat kata yang didengarnya; memisahkannya dalam kelompok bahasa berbeda; dan mempelajari bilakah dan kepada siapakah suatu bahasa digunakan. Setelah melampaui usia dua tahun, anak akan mulai berbicara. Pada usia enam tahun, anak akan memilih bahasa yang akan dikembangkan. Bahasa yang jarang digunakan akan disimpan dalam ingatannya (memorinya). Nanti, suatu saat, bahasa tersebut akan dengan mudah diingatnya jika ia mempelajari bahasa tersebut.
Dari kenyataan itu, pengajaran bahasa Indonesia tidak selalu harus diberikan sebagai bahasa pertama, melainkan sebagai bahasa kedua, setelah bahasa ibu. Menurut penelitian UNESCO, pengenalan huruf, angka, dan konsep keseharian atau lingkungan sebaiknya diberikan dalam bahasa ibu yang dikenal anak. Sebaiknya, di kelas satu hingga tiga, bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia dapat digunakan jika ada konsep yang tidak ditemukan dalam bahasa ibu. Barulah berangsur-angsur diperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Biasanya, diawali di kelas 4 dan seterusnya. Bahasa Inggris, sebagai bahasa dunia, diperkenalkan sebagai bahasa asing dan mulai diajarkan di jenjang SMP dan seterusnya. Bahasa asing lainnya, seperti Mandarin, Arab, Jerman, Perancis diajarkan mulai jenjang SMA.
Dampak Punahnya Bahasa Daerah
Penelitian terhadap Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing yang dilakukan sejak tahun 2004 oleh Linguist Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap Bahasa Daerah sangat rendah jika dibandingkan minat terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.
Kepunahan bahasa daerah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, budaya, maupun ilmiah. Beberapa dampak utama yang terjadi jika bahasa daerah punah:
Pertama, warisan budaya hilang. Bahasa adalah sarana utama untuk mengekspresikan identitas budaya, tradisi, dan sejarah suatu komunitas. Ketika sebuah bahasa punah, banyak tradisi lisan, lagu, cerita rakyat, dan pengetahuan lokal yang juga hilang. Ini menyebabkan hilangnya kekayaan budaya yang tak tergantikan.
Kedua, krisis identitas. Bahasa sering kali menjadi penanda identitas bagi suatu kelompok masyarakat. Kehilangan bahasa dapat mengakibatkan hilangnya rasa kebersamaan dan identitas kolektif, yang bisa mengarah pada penurunan rasa bangga terhadap warisan nenek moyang mereka.
Ketiga, pengetahuan lokal hilang. Bahasa daerah sering kali menyimpan pengetahuan ekologi, pengobatan tradisional, dan sistem kepercayaan yang unik. Dengan punahnya bahasa, pengetahuan berharga ini juga ikut hilang, yang bisa berdampak pada hilangnya informasi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keempat, pengaruh terhadap keanekaragaman linguistik. Keanekaragaman bahasa adalah bagian penting dari warisan manusia. Setiap bahasa menawarkan cara pandang yang unik terhadap dunia. Punahnya bahasa berarti berkurangnya variasi dalam cara manusia memahami dan berinteraksi dengan lingkungannya.
Kelima, berdampak pada psikologis dan sosial. Individu yang bahasa ibunya terancam punah atau hilang sering kali mengalami krisis identitas dan penurunan kesejahteraan psikologis. Mereka mungkin merasa kehilangan akar budaya dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan generasi sebelumnya yang hanya berbicara dalam bahasa tersebut.
Keenam, pengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan dalam bahasa ibu atau bahasa daerah memiliki peran penting dalam pembelajaran yang efektif, terutama di usia dini. Kepunahan bahasa daerah dapat menghambat proses pendidikan, terutama di komunitas yang masih bergantung pada bahasa tersebut untuk pengajaran dasar.
Ketujuh, tantangan dalam pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa membutuhkan usaha yang besar, termasuk dokumentasi, pendidikan, dan revitalisasi. Ketika bahasa semakin jarang digunakan, upaya untuk mempertahankannya menjadi lebih sulit dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas internasional.
Untuk mencegah kepunahan bahasa daerah, perlu adanya kesadaran dan tindakan kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional. Program pendidikan bilingual, dokumentasi bahasa, dan inisiatif revitalisasi bahasa adalah beberapa langkah penting yang bisa diambil untuk melestarikan bahasa-bahasa tersebut.
Daftar Bacaan
UNESCO. 2007. Improving the Quality of Mother Tongue-based Literacy and Learning: Case Studies from Asia, Africa, and South America. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education.
Felicia N. Utorodewo. 2019. https://mentarigroups.com/blog/bahasa-indonesia-bahasa-daerah-dan-bahasa-asing/ diakses 10 Juni 2024
Instagram: @linguist_id