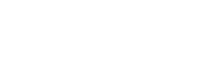Keberagaman dan Estetika Oposisi Sastra Indonesia Modern
Rafli Adi Nugroho
Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jenderal Soedirman
Kritik sastra merupakan salah satu studi penting dalam ilmu sastra yang berkaitan erat dengan ilmu sastra dan peciptaan karya sastra. Berdasarkan hal itu, penting untuk diteliti adanya kritik sastra Indonesia sampai saat ini. Sekalipun hadirnya kritik sastra Indonesia masih terbilang muda jika dibandingkan dengan kritik sastra dunia, Eropa, Amerika, dan lainnya, namun banyak sekali persoalan Sastra yang dapat diselami di dalamnya. Kritik sastra Indonesia baru berumur 100-an tahun yang kelahirannya dibersamai munculnya kesusastraan Indonesia modern sekitar tahun 1920 (Rosidi, 1964).
Adapun perkembangan sastra Indonesia modern diawali dengan munculnya roman Indonesia modern berjudul Azab dan Sengsara yang diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1921 karya Merari Siregar. Umumnya roman ini diyakini sebagai awal munculnya sastra Indonesia modern, baru setelahnya lahir majalah Pujangga Baru dan muncul juga kepustakaan-kepustakaan teori dan kritik sastra. Lahirnya karya sastra pada tahun 1920 ini menjadi pemicu banyak karya sastra diterbikan yang mana terdapat berbagai keberagaman sehingga membuat sastra Indonesia semakin berkembang.
Dalam perkembangan sastra Indonesia terdapat enam aspek penting yang mendukungnya, yaitu bahasa Indonesia, sastra Indonesia, pengarang, kondisi sosial pengarang, dan pembaca. Bahasa Indonesia berakar bahasa pada Melayu, karenanya bahasa dan sastra Indonesia lahir dalam kondisi yang dianggap sebagai hasil keputusan politik. Bahasa dan sastra Indonesia ini diputuskan dari akar kulturalnya, seolah-olah dicangkokkan atas dasar semangat nasional yang kemudian menjadi perkembangan selanjutnya. Sebagaimana dalam ilmu biologi, hasil pencangkokan akan menjadi lebih subur dibanding dengan aslinya.
Perkembangan sastra Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari peristiwa historis yang menyertainya. Penyebab banyaknya kosa kata berasal dari beragamnya kata-kata daerah dan asing yang kemudian ditunjang dengan adanya perubahan ejaan, pembentukan istilah, politik bahasa nasional, dan kongres bahasa. Sejak adanya pernyataan Kebangkitan Nasional di tahun 1920, sastra Indonesia modern lahir sebagai kelompok sastra pertama dengan nama Balai Pustaka. Pengarangnya berasal dari Sumatra yang notabennya memiliki latar belakang bahasa dan sastra Melayu. Dengan adanya semangan Ke-Indonesiaan maka perkembangan ini terus berjalan sampai sekarang.
Multikultural yang meliputi pemahan, penghargaan, dan penilaian terhadap suatu budaya menjadi sebuah doktrin atau cara pandang baru dalam memahami bahasa dan karya sastra Indonesia. Melalui bahasa dan sastra Indonesia ini, multikulturalisme menjadi pemersatu paham akan sebuah etnis dari berbagai budaya yang ada di masyarakat. Sebagaimana sebuah agama yang mengajarkan pluralisme, multikuluralisme menjadi sesuatu yang membantu memaknai pembelajaran dalam hidup bersama dalam perbedaan. Keberagaman ini kemudian memengaruhi bahasa dan sastra Indonesia modern.
Secara substansial persoalan tentang sastra Indonesia modern ini mengandung unsur budaya yang berbeda-beda, antara lain penggunaan laras budaya bahasa Indonesia, penggalian nilai budaya, pengaruh budaya asing, dan penyaringan budaya asing dalam kehidupan sastra Indonesia. Unsur-unsur tersebut kemudaian menjadi modal utama untuk menguatkan persatuan Indonesia di tengah banyaknya ancaman disintergrasi bangsa.
Bentuk sumbangan yang paling konkret dalam perkembangan sastra Indonesia adalah penggunaan bahasanya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka keseluruhan khazanah sastra terinventarisasikan dengan baik karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai khazanah sastranya. Sastralah yang benar-benar berkata secara jujur yang di dalamnya terdapat bentuk sumbangan lain yaitu berkaitan dengan isi. Sastra lama isinya identik dengan pendidikan dan pengajaran, mempelajari sastra lama sama dengan memperoleh pendidikan informal. Begitu juga dengan sastra modern yang isinya berperan dalam perkembangan mentalitas masyarakat modern yang cenderung tertarik dengan sebuah nasihat yang disampaikan secara tidak langsung. Dengan mengetahui bentuk sumbangan sastra terhadap masyarakat, maka cara kerja sastra adalah sebagai berikut:
- Teknis, berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap alokasi dana bidang pendidikan, sistem reproduksi naskah, termasuk penyebarluasannya
- Estetis, berkaitan dengan masyarakat pembaca tentang bagaimana memanfaatkannya. Apabila tidak dapat memanfaatkannya dengan baik maka celakalah bangsa ini.
Meski sudah melewati masa penjajahan dan menjadi negara merdeka, kondisi kesastraan Indonesia masih memiliki banyak kekurangan salah satunya kecilnya anggaran biaya dalam hal pendidikan di mana sastra dapat dipelajari. Di satu pihak, banyaknya karya sastra lama tetapi kurangnya minat peneliti, dan di pihak lain kurangnya penerbitan karya sastra modern tetapi minat meneliti cukup banyak. Termasuk setelah wafatnya HB Jassin, semakin berkurang dokumentasi dan kritik sastra yang menyebabkan lemahnya peningkatan masyarakat terhdapa karya sastra.
Sastra merupakan penopang perkembangan masyarakat, maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah peningkatan sastra lama dan penerbitan naskah sastra modern dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta membandingkan dengan negara tetangga yang notabenenya merdeka di waktu yang relatif bersamaan.
Sastra Indonesia modern merupakan estetika oposisi
Perbedaan estetika sastra dengan teori sastra:
- Estetika: hakikat, ciri-ciri utama karya sastra, Teori : alat untuk memahami.
- Estetika sastra adalah akibat yang diperoleh sesudah dilakukan suatu proses analisis/pemahaman dengan memanfaatkan teori sastra yang dimaksudkan. Catatan: Perlu diketahui pula, bahwa terdapat kajian ilmu tentang teori estetika yang mempelajari tentang keindahan yang mencakup sejarah, tokoh-tokoh, konsep, dan sebagainya.
- Dalam analisis karya sastra, teori sastra menggunakan penjelasan eksplisit, sedangkan estetika dipahami secara implisit. (hanya dalam penelitian yang secara khusus estetika dijelaskan secara eksplisit.)
Pemahaman tentang karya sastra:
- Secara ilmiah
- Memanfaatkan metode dan teori tertentu
- Analisis unsur-unsur karya
- Secara pragmatis
- Memanfaatkan kemampuan perasaan dan intuisi secara langsung
- Totalitas karya di mana hubungannya dengan pembaca secara umum yang masuk/larut dalam karya tersebut
Kualitas estetis bukan sebuah gejala statis, seperti pendapat Cassier (1956: 190) ketenangan karya seni adalah paradoksialnya, sebagai ketenangan yang dinamis, sebab karya seni menampilkan konflik batin yang dalam dan beraneka ragam. Sebagai akibat dari suatu proses, aspek estetis akan muncul setiap terjadinya pemahaman yang kemudian menyimpulkan suatu totalitas karya. Di dalam kaitannya dengan estetika, identitas, maupun oposisi, Teeuw (1983:15) menunjukkan tiga konvensi yang perlu diperhatikan, yaitu konvensi bahasa, konvensi sastra, dan konvensi budaya. Ketiga konvensi ini sangat erat hubungannya, namun konvensi sastralah yang paling perlu diperhatikan. Menurut Lotman, bahasa hanyalah tataran pertama yang berlapis-lapis untuk memasuki isi, ceria, dan pesan yang sesungguhnya. Memahami struktur bahasa bukan jaminan untuk memahami struktur sastranya.
Pada konvensi sastra, Teeuw menunjukkan tiga konvensi sastra, yaitu jenis sastra dengan berbagai cirinya, hakikat kreativitas imajinatif, dan hakikat otonom. Sebagai bentuk fisual, konvensi jenis membatasai wilayah pemahaman estetika, sekaligus membedakan dengan wilayah estetika yang lain. Pada aspek estetis ditentukan dengan adanya anggapan bahwa karya yang dibaca sesungguhnya bukan kenyataan, tetapi juga bukan khayalan.
Kebudayaan inilah faktor yang mengondisikan perubahan makna. Daari makna bahasa ke makna sastra dan dari tataran primer ke tataran sekunder. Dalam hubungan ini, karya merupakan salah satu sarana konservasi kebudayaan. Contohnya yaitu Novel Sitti Nurbaya, Layar Terkembang, Karya-karya N.H. Dini, dan Novel Para Priyayi. Keseluruhan karya sastra sejak periode Balai Pustaka ini, sampai saat ini mengandung berbagai informasi dan menjadi sumber data untuk memahami kebudayaan Indonesia. Ciri-ciri emansipasi dari Balai Pustaka dan Pujangga Baru, yaitu menunjukkan bahwa di Indonesia sejak abad ke-20 sudah melahirkan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Menurut Lotman, membaca karya sastra meiliki tujuan ganda, yaitu teks dengan entitas otonom sekaligus teks sebagai bagian yang lebiih bermakna, yaitu kebudayaan.
Estetika oposisi dikemukakan oleh Jurij Mikhailovich Lotman, ia membedakan estetika sastra menjadi dua, yaitu estetika identitas dan estetika oposisi. Estetika identitas mengandaikan adanya ciri-ciri yang relatif sama antara karya sastra dan pembaca. Sedangkan, estetika oposisi mengharapkan adanya perbedaan dan pertentangan bahkan secara diametral. Contoh estetika identitas adalah folklore, sastra klasik, sastra abad pertengahan, sastra Asia kuno. Contoh estetika oposisi adalah romantisisme, realisme, dan sastra garda depan. Estetika identitas berperan dalam masyarakat sebagai daya sentripetal yang membutuhkan suatu komunitas. Sementara estetika oposisi berperan sebagai daya sentripugal dalam masyarakat dalam bentuk individual.
Estetika Lotman memiliki nilai estetis tidak tetap, berubah terus-menerus berdasarkan hubungan antara karya sastra dan pembaca, berkembang atas dasar saling mempengaruhi antar tradisi astistik dengan konteks sosial. Di luar estetika Lotman, nilai estetis didasarkan oleh kemampuannya dalam mempertahankan norma, kualitas estetis dicapai melalui hubungan antara aspek semantis dengan aspek formal. Sastra Indonesia modern termasuk dalam estetika oposisi sebab sejak kelahirannya telah berisi ciri-ciri sastra Barat modern dan para pengarang di zaman sastra Indonesia modern memiliki paradigma bahwa karya yang dihasilkan harus berbeda dengan karya-karya yang sudah ada.
Ada beberapa istilah dalam bidang sastra dan psikologi yang memiliki makna baru dalam teori kontemporer. Pertama interteks yaitu memandang bahwa setiap teks merupakan tiruan dari teks lain, kedua ada ruang kosong, ketiga ada kematian pengarang, keempat pastiche yang mirip dengan interteks, diperoleh dengan cara meniru teks masa lalu yang bertujuan untuk memberikan apresiasi, kelima parodi yang bisa berfungsi sebagai kritik, kecaman, dan sindiran, keenam kitsch, ketujuh camp, dan terakhir schizhophrenia.
Menurut Lotman, estetika oposisi berkembang sejak zaman Renaissance. Sesuai dengan ciri-ciri manusia yang ingin mendapatkan kebebasan penuh, maka jelas yang dilukiskan dalam karya sastra adalah pembaruan, kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Bangsa Indonesia seolah-olah baru bangun setelah berabad-abad berada di bawah kekasaan kolonial. Dengan adanya kebebasan, maka para seniman secara serentak bangkit membangun bangsa dengan menggunakan kekuatan bahasanya yang kemudian dituangkan ke dalam genre baru yang dianggap sebagai menampilkan oposisi dengan genre terdahulu. Pengangkatan bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia merupakan bukti pertama adanya usaha untuk menampilkan estetika oposisi.
Estetika oposisi sudah berfungsi sejak awal pertumbuhan sastra Indonesia modern, awal abad ke-20, sejak Balai Pustaka dan Pujangga Baru hingga sekarang. Bisa dilihat dari aspek bentuk, karya sastra Balai Pustaka sudah menggunakan genre roman, novel, cerpen, puisi bebas, dan drama bersajak. Dari aspek isi sudah memasukkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti: adat istiadat, kawin paksa, nasionalisme, dan masalah rumah tangga. Sastra Indonesia awal ini juga memasukkan masalah mengenai perlawanan kaum perempuan, emansipasi, meskipun umumnya mengalami kegagalan. Di samping itu karya sastra sudah memuat perkawinan antarbangsa seperti Salah Asuhan. Contoh estetika oposisi dalam perkembangan sastra Indonesia:
- Novel Belenggu karya Armijn Pane dengan tema keretakan rumah tangga yang disajikan secara pornografis dengan teknik arus kesadara. Dalam novel belenggu-lah tampil ciri-ciri oposisi yang sangat menonjol sehingga novel tersebut dikatakan sebagai melampaui zamannya.
- Dalam puisi yang ditonjolkan adalah individualisme seperti pada puisi karya Amir Hamzah, Sanusi Pane, dan Chairil Anwar.
- Teknik antiplot dan antitokoh oleh Iwan Simatupang dan Putu Wijaya
- Tahun 1970-an, pengarang kembali melukiskan latar lokal dalam karyanya (setelah tiga dasawarsa melukiskan geografis mancanegara) dengan maksud menampilkan aspek wilayah tertentu. Contohnya dalam karya Ahmad Tohari yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, Jentera Bianglala, karya Umar Kayam yaitu Sri Sumarah, Bawuk, Para Priyayi.
Daftar Bacaan
Rosidi, Ajio. 1964. Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir? Bhratara: Jakarta.
Cassirer, Ernst. 1956. Determinism and Indeterminism in Modern Physics: Historical and Systematic Studies of the Problem of Causality. Translated by Otto Theodor Benfey. New Haven, CT: Yale University Press.
Teeuw, A. 1983. Membaca dan Menilai karya Sastra. Jakarta: Gramedia.
Tentang Penulis
Rafli Adi Nugroho lahir di Banyumas 7 Juli 2001. Penulis merupakan mahasiswa program studi Sastra Indonesia Universitas Jenderal Soedirman dan Relawan Pustaka di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Karya berupa artikel dan puisi telah publish di media cetak dan online.